A Woman’s Jouney

Sejujurnya, gue gak selalu bahagia menjadi seorang cewek. Lama gue berpikir bahwa seorang cewek adalah makhluk inferior. Kalangan yang lemah dan punya disadvantage bawaan sejak lahir yang bikin dia lebih rendah daripada yang lain. Lebih lemah secara fisik, lebih rentan terhadap pelecehan, lebih mudah terpengaruh secara emosional. Intinya, jadi cewek itu adalah kelemahan.
Butuh waktu buat gue merangkul jati diri gue sebagai seorang wanita. Butuh proses hidup yang panjang buat gue mensyukuri apa yang gue punya dan enggak menganggapnya sebagai sebuah kelemahan lagi. Let me tell you my journey.
The Little Girl Who Stands Up For Her Friend
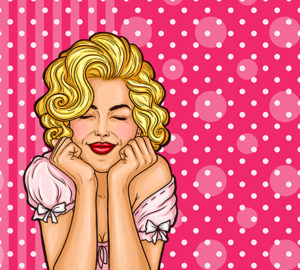 Waktu gue SD, ada sebuah kejadian di mana gue lagi ngebelain teman gue yang lagi ditindas. Gue bahkan udah lupa siapa yang gue bela, dan karena apa. Tapi gue masih ingat siapa yang menindas teman gue itu dan apa akibatnya terhadap gue.
Waktu gue SD, ada sebuah kejadian di mana gue lagi ngebelain teman gue yang lagi ditindas. Gue bahkan udah lupa siapa yang gue bela, dan karena apa. Tapi gue masih ingat siapa yang menindas teman gue itu dan apa akibatnya terhadap gue.
Si pem-bully adalah seorang anak cowok yang satu tahun lebih tua dari gue. Dia adalah kakak teman sekelas gue. Waktu itu kejadiannya di jam istirahat, di dalam kelas. Gue ingat dia suru gue minggir. Tapi gue gak mau. Dia teriakin gue, dan ngancam bakal pukul gue kalau gue gak minggir. Lalu gue tantangin dia untuk pukul gue aja kalau berani.
Terus lo tahu apa yang terjadi? Gue pikir, yang namanya cowok, udah kodratnya enggak boleh pukul cewek. Makanya gue pikir tantangan gue tuh cuma bullshit doang. Gue gak berharap dipukul lah! Gue pikir dia bakal nyerah dan pergi.
Tapi gak gitu kejadiannya, girls. Dia dorong gue keras banget di dada. Gue ingat rasa sakitnya. Dan betapa kecewanya gue terhadap perlakuan itu. Tapi setelah itu dia pergi. Dan berhenti menindas teman gue.
Satu sisi, gue bangga karena gue berhasil ngebelain teman gue. Di sisi lain, anak cewek kecil yang baru berumur 10 tahun ini baru sadar bahwa yang namanya cowok, gak semuanya ngerti gimana caranya bertindak sebagai seorang cowok.
Damn! I wish I were a boy so I can hit him back. Because a girl shouldn’t hit anyone ever. Right? Even when I’m being hit first.
Yikes! I Hate Pink!

Gue gak bilang kejadian ini adalah groundbreaking moment buat gue. Bukan juga moment yang mendefinisikan hidup gue secara keseluruhan juga. Gue bahkan baru ingat kejadian itu waktu gue nulis artikel ini. But here is the thing. This small accident is one of many accidents that turns my perspective about womanhood.
Di satu sisi gue adalah seorang cewek. Gue di-expect untuk bertindak seperti seorang cewek. Dengan kulit wajah yang halus dan mulus. Rajin perawatan. Pakai masker tiap malam biar gak jerawatan. Ke salon seminggu sekali. Menjaga berat badan dan penampilan. Jago pakai make up yang bikin gue makin cetar. And so on. And so on…
Pada kenyataannya, gue benci ngelakuin itu semua. Gue males pakai masker, kecuali jerawat gue udah gak ketolongan banyaknya. Gue bahkan males pakai obat jerawat ketika bentol merah itu mulai muncul di muka gue. Biasanya gue diemin aja. Ntar juga kempes sendiri. Haha!
And you know what? For many years I hate the color PINK! I hate it so much!
Karena menurut gue, warna pink itu terlalu cewek banget. Warna yang sexist. Warna yang centil dan norak. Warna yang enggak menunjukkan kekuatan sama sekali. Terlalu unyu. Terlalu lenje. Terlalu lemah.
Pokoknya gue adalah seorang cewek yang menolak untuk tampil terlalu cewek. Gue pada dasarnya gak tomboy. Gue masih suka pakai rok. Gue masih suka panjangin rambut. Tapi gue menolak tampil seperti seorang princess. That is just not me.
What Is So Wrong About That?
 Well, it’s not wrong. It’s just…. Not embracing who I am.
Well, it’s not wrong. It’s just…. Not embracing who I am.
Kita dilahirkan dengan berbagai atribut yang gak bisa kita pilih. Beberapa atribut mungkin bisa kita ubah seiring perjalanan waktu, batasannya cuma etika yang kita pegang aja. Tapi buat gue, atribut-atribut bawaan lahir ini adalah given from above. Meaning that, God give it to me as a present. Sebuah hadiah. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang berguna.
(Iya dong, mana ada orang yang kasih kado yang jelek dan gak berguna. Ya kan? Apalagi kalau Tuhan yang kasih.)
So I don’t want to change that. I don’t want to deny who I am. Not even a little bit.
Gue pengen jadi cewek yang bangga jadi seorang cewek. I don’t want any ounce of denial inside my heart. I want to embrace it and be happy for it.
The Turning Point
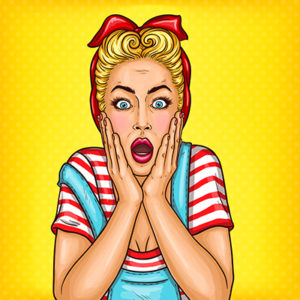 Waktu gue tahu gue akan punya anak cewek, gue bilang sama suami gue.
Waktu gue tahu gue akan punya anak cewek, gue bilang sama suami gue.
“Wah. Anak cewek. Kamu harus lebih jagain dia ya.”
And he doesn’t actually get it. Kenapa harus dijagain? Ya sama aja lah anak cewek sama anak cowok. Dua-duanya harus dijagain.
Ya, benar. Tapi cowok mana pun gak pernah ngalamin rasanya hidup jadi seorang cewek. Segala pandangan umum berbasis patriarki di masyarakat yang udah mendarah daging sering melemahkan seorang cewek, gak peduli seberapa keras pun dia berusaha.
Well, salah satu contohnya, gue pernah kerja di lingkungan yang mayoritas adalah cowok, dan manager gue saat itu dengan gamblang ngomong, “Iya gue butuh cewek nih di tim gue. Biar bisa lebih PDKT sama klien.” (– yang mana kliennya waktu itu kebanyakan cowok.)
Apa gak bikin gue ngerasa jadi kayak umpan yang dipasang di ujung tali pancingan waktu diomongin begitu? Pastinya iya. Tapi butuh waktu beberapa bulan buat gue sadar bahwa hal ini mengganggu banget buat gue. Sampai akhirnya setelah 3 bulan gue minta keluar dari project itu. Bukan cuma karena hal ini aja sih. Tapi ini juga adalah salah satu faktor utamanya.
Anyway, balik lagi ke turning point gue. Pada intinya, gue mulai berubah sejak gue mendekap anak perempuan gue yang super cantik dan menggemaskan. Gue sayang banget sama dia. Gue gak pengen dia mengalami segala pengalamn buruk yang pernah gue alami gara-gara pola pandang gue yang salah soal womanhood.
Makanya, terus menyangkal sebagian diri gue bukanlah sebuah contoh yang baik buat anak perempuan gue. I have to be a good example for her. I have to show her how to be 100% woman and 100% strong. Bukan dengan melakukannya setengah-setengah. Bukan dengan berusaha menjadi orang lain. Tapi dengan benar-benar menjadi diri sendiri apa adanya, menerima semuanya dengan rasa syukur dan bahagia akan semuanya itu.
And Now I’m Happily Loves Pink
 Maka sekarang gue gak lagi membenci pink. Gue dengan senang hati akan memakai baju warna pink kalau memang modelnya bagus, potongannya cocok di badan gue dan coraknya gak norak.
Maka sekarang gue gak lagi membenci pink. Gue dengan senang hati akan memakai baju warna pink kalau memang modelnya bagus, potongannya cocok di badan gue dan coraknya gak norak.
Dan tahu gak apa lagi yang berubah? Gue jadi lebih suka pakai rok sekarang. Bosan pakai celana panjang melulu. Kalau dulu gue cuma pakai rok kalau diharuskan atau gak ada pilihan lain (– misalnya kalau celana pada belum kering), sekarang gue dengan senang hati pakai rok kalau itu bikin outfit gue makin chic.
Gue juga sadar satu hal lagi. Bahwa gak semua stigma soal perempuan benar-benar mendefinisikan seorang perempuan. Kayak misalnya, cewek itu harus maskeran, perawatan, ke salon rutin dll kayak yang gue sebut di atas. Well, gue bisa aja gak melakukan semua itu dan masih tetap 100% cewek kok.
Because womanhood is about the inside. It’s not about what we see on the outside. Media makes us think that way. When the truth is, we can be 100% girls while being a brilliant technician wearing an ugly jumpsuit with so many pimples on our face.
Took me a while to realise that. But now I know better. And I will not be held back by those stigma.
I’m a girl. And I’m proud of being a girl.
Being a girl is not necessarily being weak. Instead, being strong despite of those weaknesses.
Spread love,
hiLda



